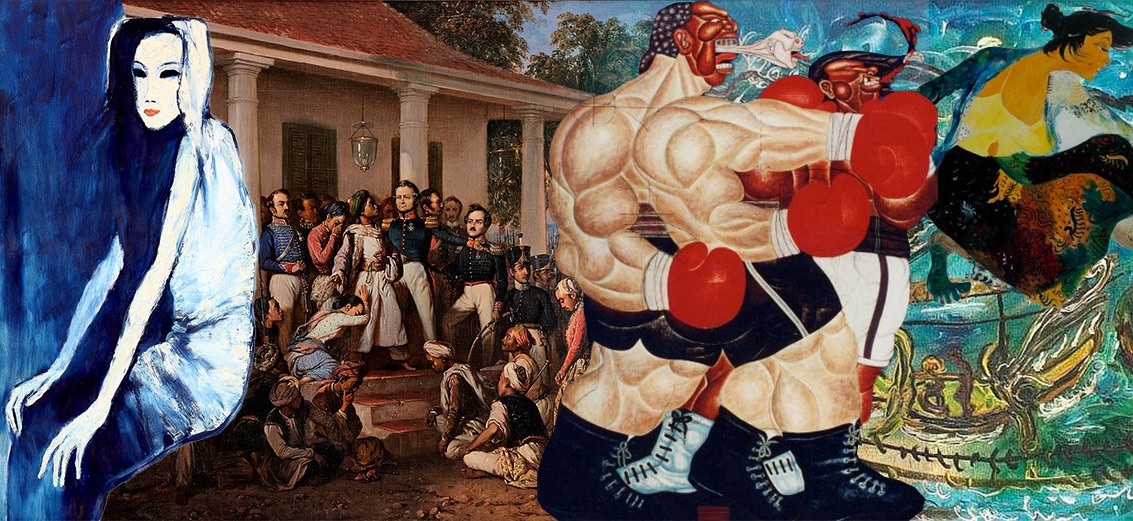Kelas XI
(Pendidikan Pancasila, Kurikulum Merdeka Revisi 2023) tentang Perilaku
Demokratis Berdasarkan Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI ’45) pada Era Keterbukaan Informasi — yang diuraikan dalam dua
bagian: (1) Makna Demokratis, dan (2) Perilaku Demokratis pada Era Keterbukaan
Informasi. Materi ini disusun agar cocok sebagai bahan ajar atau ringkasan
untuk peserta didik.
1. Makna Demokratis
a)
Pengertian Demokrasi
- Kata “demokrasi” berasal
dari bahasa Yunani: demos (“rakyat”) + kratos (“kekuasaan”
atau “pemerintahan”) → secara harfiah “pemerintahan oleh rakyat”.
- Dalam konteks Indonesia,
demokrasi bukan saja sistem politik, tetapi juga cara berpikir, bersikap
dan bertindak yang menjamin bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dan
diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
- Dengan demikian, makna
demokratis berkaitan dengan sikap dan perilaku warga yang menghargai
persamaan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan musyawarah dalam
pengambilan keputusan.
b)
Demokrasi dalam kerangka UUD NRI ’45
- UUD NRI ’45 sebagai konstitusi
negara Indonesia memberi landasan hukum bagi demokrasi di Indonesia,
misalnya melalui pasal-pasal yang menjamin hak kebebasan berpendapat,
kebebasan memperoleh informasi, dan partisipasi rakyat.
- Demokrasi berdasarkan UUD
’45 memiliki ciri: kedaulatan rakyat, supremasi hukum, penghormatan
terhadap hak asasi manusia (HAM), serta perwujudan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
- Dalam buku Pendidikan
Pancasila kelas XI Kurikulum Merdeka dijelaskan bahwa materi demokrasi
berdasarkan UUD ’45 mencakup “Perilaku Demokratis Berdasarkan UUD NRI
Tahun 1945 pada Era Keterbukaan Informasi”.
c)
Nilai-nilai Dasar Demokrasi
Beberapa
nilai penting yang melekat dalam demokrasi Pancasila, antara lain:
- Persamaan hak dan kewajiban
seluruh warga negara.
- Kebebasan untuk berpendapat
dan memperoleh informasi, namun diiringi dengan tanggung jawab.
- Musyawarah dan mufakat
sebagai metode dalam pengambilan keputusan bersama.
- Toleransi terhadap
keberagaman serta penghormatan antarwarga negara
d)
Relevansi Makna Demokratis saat ini
- Di era informasi (digital),
demokrasi menuntut tidak hanya prosedur formal seperti pemilihan umum,
tetapi juga kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi yang benar,
serta literasi kritis untuk menyaring informasi
- Perilaku demokratis harus
ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari: di sekolah, keluarga, lingkungan
masyarakat, hingga di ruang digital (sosial media, forum online).
2. Perilaku Demokratis pada Era Keterbukaan
Informasi
a) Apa
yang dimaksud “Era Keterbukaan Informasi”?
- Era keterbukaan informasi
merujuk pada kondisi di mana arus informasi menjadi sangat cepat dan luas
(termasuk melalui internet, media sosial, portal berita), sehingga akses
masyarakat terhadap informasi meningkat secara signifikan.
- Namun di sisi lain, hal ini
juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi palsu (hoaks),
manipulasi opini publik, dan tantangan dalam menjaga keutuhan nasional
akibat provokasi lewat media informasi.
b)
Landasan UUD NRI ’45 yang mendukung perilaku demokratis di era ini
- Misalnya, pasal-pasal dalam
UUD ’45 yang menyebutkan hak atas kebebasan berpendapat dan memperoleh
informasi.
- Dengan demikian, warga
negara memiliki hak untuk mengakses informasi dan menyampaikan pendapatnya
— tetapi juga dibutuhkan perilaku yang sesuai dengan nilai demokratis agar
tidak merusak kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
c) Contoh
Perilaku Demokratis yang relevan di era keterbukaan informasi
Berikut
beberapa contoh perilaku yang sesuai:
- Menghargai hak orang lain
untuk berpendapat
- Dalam forum diskusi online
atau offline, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara
dan mendengarkan pendapat mereka tanpa memotong secara kasar.
- Menjawab/memproses informasi
dengan sikap kritis
- Sebelum membagikan atau
menanggapi informasi di media sosial, melakukan cek kebenaran
(fact-checking) apakah informasi tersebut benar atau tidak.
- Tidak menyebarkan hoaks,
provokasi, ujaran kebencian, atau konten yang memecah belah.
- Menggunakan saluran resmi
dan tata cara yang baik dalam menyampaikan pendapat
- Menyampaikan opini secara
santun, dengan argumen yang jelas, dan menghormati aturan serta norma
yang berlaku.
- Aktif partisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat yang berbasis informasi
- Misalnya ikut serta dalam
forum publik, survei, atau diskusi yang diadakan secara daring atau
luring, menyampaikan aspirasi warga secara konstruktif.
- Menggunakan media sosial
atau platform digital untuk menyebarkan informasi yang positif dan
membangun demokrasi, bukan untuk memecah belah.
- Tanggung jawab atas
kebebasan informasi
- Kebebasan memperoleh dan
menyebarkan informasi harus diiringi dengan tanggung jawab: tidak
menyalahgunakan posisi atau media untuk menyebar fitnah, ujaran
kebencian, atau disinformasi.
- Kesadaran bahwa kebebasan
tidak absolut; ada batasan yang ditentukan oleh hukum, etika, dan norma
sosial.
d)
Hubungan Perilaku Demokratis dengan UUD NRI ’45 di Era Informasi
- Dengan kebebasan memperoleh
informasi dan menyampaikan pendapat yang dilindungi konstitusi, warga
negara berada pada posisi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan
demokratis.
- Jika warga negara mampu
bertindak demokratis di era keterbukaan informasi, maka prinsip-prinsip
demokrasi yang diamanatkan UUD NRI ’45 dapat terwujud secara nyata:
misalnya pengambilan keputusan yang partisipatif, transparansi,
akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM.
- Sebaliknya, jika kebebasan
informasi tidak diiringi dengan perilaku demokratis, bisa terjadi
penyalahgunaan: misalnya hoaks, polarisasi masyarakat, konflik sosial.
e)
Tantangan dan Upaya Pemecahan
Tantangan
- Maraknya hoaks dan
disinformasi yang dapat menggoyahkan kepercayaan publik dan persatuan
bangsa.
- Ketidakmampuan sebagian
warga negara dalam menyaring informasi atau kritis terhadap sumber
informasi.
- Ketidaksantunan dalam
bermedia sosial: ujaran kebencian, menyinggung suku/agama/orang lain,
menyebar penghakiman tanpa bukti.
- Ketidakseimbangan antara kebebasan
berpendapat dan kewajiban bermasyarakat (misalnya terlalu bebas tanpa
mempertimbangkan akibat sosial).
Upaya
Pemecahan
- Meningkatkan literasi
digital dan literasi media di kalangan siswa, masyarakat agar bisa
membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi hoaks, dan menggunakan media
sosial secara bertanggung jawab.
- Menumbuhkan budaya
musyawarah dan dialog di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat untuk
membiasakan perilaku mendengarkan, menghormati, dan mengambil keputusan
bersama.
- Menguatkan nilai-nilai
demokrasi dalam pembelajaran, aktivitas sekolah dan komunitas: misalnya
debat yang sehat, forum siswa, diskusi publik.
- Memanfaatkan media digital
untuk kegiatan positif: kampanye informasi benar, diskusi terbuka,
penyebaran nilai demokratis.
- Guru, sekolah dan keluarga
sebagai agen pembimbing: memberikan contoh konkret perilaku demokratis dan
mengajak siswa untuk refleksi terhadap penggunaan informasi.
f)
Ringkasan Perilaku Demokratis yang Diharapkan
- Berani menyampaikan pendapat
dan menerima pendapat orang lain dengan sikap terbuka dan santun.
- Aktif mencari dan
menyebarkan informasi yang benar serta konstruktif.
- Mampu menggunakan media
digital secara kritis dan bertanggung jawab.
- Menghormati keberagaman
pendapat, latar belakang, budaya, dan agama.
- Berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan secara bersama (musyawarah) atau menggunakan saluran
demokratis.
- Memprioritaskan kepentingan
bersama, bukan semata kepentingan pribadi atau kelompok kecil.
- Menjaga integritas, keadilan
dan akuntabilitas dalam bertindak sebagai warga negara digital.